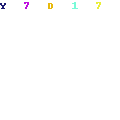1. CAHAYA
Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sebagai sumber energi utama bagi ekosistem. Ada tiga aspek penting yang perlu dikaji dari faktor cahaya, yang sangat erat kaitannya dengan sistem ekologi, yaitu:
· Kualitas cahaya atau komposisi panjang gelombang.
· Intensitas cahaya atau kandungan energi dari cahaya.
· Lama penyinaran, seperti panjang hari atau jumlah jam cahaya yang bersinar setiap hari.
1. Kualitas Cahaya
Secara fisika, radiasi matahari merupakan gelombang- gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang. Tidak semua gelombang- gelombang tadi dapat menembus lapisan atas atmosfer untuk mencapai permukaan bumi. Umumnya kualitas cahaya tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga tidak selalu merupakan faktor ekologi yang penting.
Umumnya tumbuhan teradaptasi untuk mengelola cahaya dengan panjang gelombang antara 0,39 – 7,6 mikron. Klorofil yang berwarna hijau mengasorpsi cahaya merah dan biru, dengan demikian panjang gelombang itulah yang merupakan bagian dari spectrum cahaya yang sangat bermanfaat bagi fotosintesis.
Pada ekosistem daratan kualitas cahaya tidak mempunyai variasi yang berarti untuk mempengaruhi fotosintesis. Pada ekosistem perairan, cahaya merah dan biru diserap fitoplankton yang hidup di permukaan sehingga cahaya hijau akal lewat atau dipenetrasikan ke lapisan lebih bawah dan sangat sulit untuk diserap oleh fitoplankton.
Pengaruh dari cahaya ultraviolet terhadap tumbuhan masih belum jelas. Yang jelas cahaya ini dapat merusak atau membunuh bacteria dan mampu mempengaruhi perkembangan tumbuhan (menjadi terhambat), contohnya yaitu bentuk- bentuk daun yang roset, terhambatnya batang menjadi panjang
2. Intensitas cahaya
Intensitas cahaya atau kandungan energi merupakan aspek cahaya terpenting sebagai faktor lingkungan, karena berperan sebagai tenaga pengendali utama dari ekosistem. Intensitas cahaya ini sangat bervariasi baik dalam ruang/ spasial maupun dalam waktu/temporal.
Intensitas cahaya terbesar terjadi di daerah tropika, terutama daerah kering (zona arid), sedikit cahaya yang direfleksikan oleh awan. Di daerah garis lintang rendah, cahaya matahari menembus atmosfer dan membentuk sudut yang besar dengan permukaan bumi. Sehingga lapisan atmosfer yang tembus berada dalam ketebalan minimum.
Intensitas cahaya menurun secara cepat dengan naiknya garis lintang. Pada garis lintang yang tinggi matahari berada pada sudut yang rendah terhadap permukaan bumi dan permukaan atmosfer, dengan demikian sinar menembus lapisan atmosfer yang terpanjang ini akan mengakibatkan lebih banyak cahaya yang direfleksikan dan dihamburkan oleh lapisan awan dan pencemar di atmosfer.
v Kepentingan Intensitas Cahaya
Intensitas cahaya dalam suatu ekosistem adalah bervariasi. Kanopi suatu vegetasi akan menahan dann mengabsorpsi sejumlah cahaya sehingga ini akan menentukan jumlah cahaya yang mampu menembus dan merupakan sejumlah energi yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dasar. Intensitas cahaya yang berlebihan dapat berperan sebagai faktor pembatas. Cahaya yang kuat sekali dapat merusak enzim akibat foto- oksidasi, ini menganggu metabolisme organisme terutama kemampuan di dalam mensisntesis protein.
v Titik Kompensasi
Dengan tujuan untuk menghasilkan produktivitas bersih, tumbuhan harus menerima sejumlah cahaya yang cukup untuk membentuk karbohidrat yang memadai dalam mengimbangi kehilangan sejumlah karbohidrat akibat respirasi. Apabila semua faktor- faktor lainnya mempengaruhi laju fotosintesis dan respirasi diasumsikan konstan, keseimbangan antara kedua proses tadi akan tercapai pada sejumlah intensitas cahaya tertentu.
Harga intensitas cahaya dengan laju fotosintesis (pembentukan karbohidrat), dapat mengimbangi kehilangan karbohidrat akibat respirasi dikenal sebagai titik kompensasi. Harga titik kompensasi ini akan berlainan untuk setiap jenis tumbuhan.
v Heliofita dan Siofita
Tumbuhan yang teradaptasi untuk hidup pada tempat –tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi disebut tumbuhan heliofita. Sebaliknya tumbuhan yang hidup baik dalam situasi jumlah cahaya yang rendah, dengan titik kompensasi yang rendah pula disebut tumbuhan yang senang teduh (siofita), metabolisme dan respirasinya lambat. Salah satu yang membedakan tumbuhan heliofita dengan siofita adalah tumbuhan heliofita memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk klorofil.
v Cahaya Optimal bagi Tumbuhan
Kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan terpenuhi bila cahaya melebihi titik kompensasinya.
v Adaptasi Tumbuhan terhadap Cahaya Kuat
Beberapa tumbuhan mempunyai karakteristika yang dianggap sebagai adaptasinya dalam mereduksi kerusakan akibat cahaya yang terlalu kuat atau supraoptimal. Dedaunan yang mendapat cahaya dengan intensitas yang tinggi, kloroplasnya berbentuk cakram, posisinya sedemikian rupa sehingga cahaya yang diterima hanya oleh dinding vertikalnya. Antosianin berperan sebagai pemantul cahaya sehingga menghambat atau mengurangi penembusan cahaya ke jaringan yang lebih dalam.
3. Lama Penyinaran
Lama penyinaran relative antara siang dan malam dalam 24 jam akan mempengaruhi fisiologis dari tumbuhan. Fotoperiodisme adalah respon dari suatu organisme terhadap lamanya penyinaran sinar matahari. Contoh dari fotoperiodisme adalah perbungaan, jatuhnya daun, dan dormansi.
Di daerah sepanjang khatulistiwa lamanya siang hari atau fotoperiodisme akan konstan sepanjang tahun, sekitar 12 jam. Di daerah temperata/ bermusim panjang hari lebih dari 12 jam pada musim panas, tetapi akan kurang dari 12 jam pada musim dingin.
Berdasarkan responnya terhadap periode siang dan malam, tumbungan berbunga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
v Tumbuhan berkala panjang
Tumbuhan yang memerlukan lamanya siang hari lebih dari 12 jam untuk terjadinya proses perbungaan, seperti gandum, bayam, dll.
v Tumbuhan berkala pendek
Tumbuhan yang memerlukan lamanya siang lebih pendek dari 12 jam untuk terjadinya proses perbungaan, seperti tembakau dan bunga krisan.
v Tumbuhan berhari netral
Tumbuhan yang tidak memerlukan periode panjang hari tertentu untuk proses perbungaannya, misalnya tomat.
Apabila beberapa tumbuhan terpaksa harus hidup di kondisi fotoperiodisme yang tidak optimal, maka pertumbuhannya akan bergeser ke pertumbuhan vegetatif. Di daerah khatulistiwa, tingkah laku tumbuhan sehubungan dengan fotoperiodisme ini tidaklah menunjukkan adanya pengaruh yang mencolok. Tumbuhan akan tetap aktif dan berbunga sepanjang tahun asalkan faktor- faktor lainnya dalam hal ini suhu, air, dan nutrisi tidak merupakan faktor pembatas.
2. SUHU
Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Suhu dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Rai dkk (1998) suhu dapat berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut, sedangkan berperan tidak langsung dengan mempengaruhi faktor-faktor lainnya terutama suplai air. Suhu akan mempengaruhi laju evaporasi dan menyebabkan tidak saja keefektifan hujan tetapi juga laju kehilangan air dari organisme.
Sebenarnya sangat sulit untuk memisahkan secara mandiri pengaruh suhu sebagai faktor lingkungan. Misalnya energi cahaya mungkin diubah menjadi energi panas ketika cahaya diabsorpsi oleh suatu substansi. Suhu sering berperan bersamaan dengan cahaya dan air untuk mengontrol fungsi- fungsi dari organisme.
Relatif mudah untuk mengukur suhu dalam suatu lingkungan tetapi sulit untuk menentukan suhu yang bagaimana yang berperan nyata, apakah keadaan maksimum, minimum atau keadaan harga rata- ratanya yang penting.
1. Variasi suhu
Sangat sedikit tempat- tempat di permukaan bumi secara terus- menerus berada dalam kondisi terlalu panas atau terlalu dingin untuk sistem kehidupan, suhu biasanya mempunyai variasi baik secara ruang maupun secara waktu. Variasi suhu ini berkaitan dengan garis lintang, dan sejalan dengan ini juga terjadi variasi local berdasarkan topografi dan jarak dari laut.
Terjadi juga variasi dari suhu ini dalam ekosistem, misalnya dalam hutan dan ekosistem perairan. Perbedaan yang nyata antara suhu pada permukaan kanopi hutan dengan suhu di bagian dasar hutan akan terlihat dengan jelas. Demikian juga perbedaan suhu berdasarkan kedalaman air.
Seperti halnya dengan faktor cahaya, letak dari sumber panas ( matahari ), bersama- sama dengan putarannya bumi pada porosnya akan menimbulkan variasi suhu di alam tempat tumbuhan hidup.
Jumlah panas yang diterima bumi juga berubah- ubah setiap saat tergantung pada lintasan awan, bayangan tumbuhan setiap hari, setiap tahun dan gejala geologi.
Begitu matahari terbit pagi hari, permukaan bumi mulai memperoleh lebih banyak panas dibandingkan dengan yang hilang karena radiasi panas bumi, dengan demikian suhu akan naik dengan cepat. Setelah beberapa jam tercapailah suhu yang tinggi sekitar tengah hari, setelah lewat petang mulailah terjadi penurunan suhu maka bumi ini akibat reradiasi yang lebih besar dibandingkan dengan radiasi yang diterima. Pada malam hari penurunan suhu muka bumi akan bertambah lagi, panas yang diterima melalui radiasi dari matahari tidak ada, sedangkan reradiasi berjalan terus, akibatnya ada kemungkinan suhu permukaan bumi lebih rendah dari suhu udara disekitarnya. Proses ini akan menimbulkan fluktuasi suhu seharian, dan fluktuasi suhu yang paling tinggi akan terjadi di daerah antara ombak di tepi pantai.
Berbagai karakteristika muka bumi penyebab variasi suhu :
- Komposisi dan warna tanah, makin terang warna tanah makin banyak panas yang dipantulkan, makin gelap warna tanah makin banyak panas yang diserap.
- Kegemburan dan kadar air tanah, tanah yang gembur lebih cepat memberikan respon pada pancaran panas daripada tanah yang padat, terutama erat kaitannya dengan penembusan dan kadar air tanah, makin basah tanah makin lambat suhu berubah.
- Kerimbunan Tumbuhan, pada situasi dimana udara mampu bergerak dengan bebas maka tidak ada perbedaan suhu antara tempat terbuka dengan tempat tertutup vegetasi. Tetapi kalau angin tidak menghembus keadaan sangat berlainan, dengan kerimbunan yang rendah mampu mereduksi pemanasan tanah oleh pemancaran sinar matahari. Ditambah lagi kelembaban udara dibawah rimbunan tumbuhan akan menambah banyaknya panas yang dipakai untuk pemanasan uap air, akibatnya akan menaikan suhu udara. Pada malam hari panas yang dipancaran kembali oleh tanah akan tertahan oleh lapisan kanopi, dengan demikian fluktuasi suhu dalam hutan sering jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan fluktuasi di tempat terbuka atau tidak bervegetasi.
- Iklim mikro perkotaan, perkembangan suatu kota menunjukkan adanya pengaruh terhadap iklim mikro. Asap dan gas yang terdapat di udara kota sering mereduksi radiasi. Partikel- partikel debu yang melayang di udara merupakan inti dari uap air dalam proses kondensasinya uap air inilah yang bersifat aktif dalam mengurangi pengaruh radiasi matahari tadi.
- Kemiringan lereng dan garis lintang, kemiringan lereng sebesar 50 dapat mereduksi suhu sebanding dengan 450 km perjalanan arah ke kutub.
Variasi suhu berdasarkan waktu/ temporal terjadi baik musiman maupun harian, kesemua variasi ini akan mempengaruhi penyebaran dan fungsi tumbuhan.
- Suhu dan Tumbuhan
Kehidupan di muka bumi ini berada dalam suatu bahan kisaran suhu antara 00 C sampai dengan 500 C, dalam kisaran suhu ini individu tumbuhan mempunyai suhu minimum, maksimum dan optimum yang diperlukan untuk aktifitas metabolismenya. Suhu- suhu tadi yang diperlukan organisme hidup dikenal dengan suhu kardinal.
Suhu tumbuhan biasanya kurang lebih sama dengan suhu sekitarnya karena adanya pertukaran suhu yang terus- menerus antara tumbuhan dengan udara sekitarnya.
Kisaran toleransi suhu bagi tumbuhan sangat bevariasi, untuk tanaman di tropika, semangka, tidak dapat mentoleransi suhu di bawah 150 – 180 C, sedangkan untuk biji- bijian tidak bisa hidup dengan suhu di bawah minus 20 C – minus 50 C. Sebaliknya konifer di daerah temperata masih bisa mentoleransi suhu sampai serendah minus 300 C. Tumbuhan air umumnya mempunyai kisaran toleransi suhu yang lebih sempit jika dibandingkan dengan tumbuhan di daratan.
Secara garis besar semua tumbuhan mempunyai kisaran toleransi terhadap suhu yang berbeda tergantung pada umur, keseimbangan air dan juga keadaan musim.
3. AIR
Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apa pun juga. Tanpa air seluruh organisme tidak akan dapat hidup. Bagi tumbuhan, air mempunyai peranan yang penting karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Adanya air tergantung dari curah hujan dan curah hujan sangat tergantung dari iklim di daerah yang bersangkutan.
Air menutupi sekitar 70% permukaan bumi, dengan jumlah sekitar 1.368 juta km3. Air terdapat dalam berbagai bentuk, misalnya uap air, es, cairan dan salju. Air tawar terutama terdapat di danau, sungai, air tanah (ground water) dan gunung es (glacier). Semua badan air di daratan dihubungkan dengan laut dan atmosfer melalui siklus hidrologi yang berlangsung secara kontinu (Effendi, 2003).
a. Sifat air
Menurut Benyamin Lakitan (2001) dan Hefni Effendi (2003) air memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh senyawa kimia yang lain, yaitu.
1. Berbentuk cair pada suhu ruang. Semakin besar ukuran molekul suatu senyawa maka pada suhu ruang senyawa tersebut akan cenderung berbentuk cair. Sebaliknya jika ukurannya kecil maka akan cenderung berbentuk gas.`Air yang berat molekulnya sebesar 18 gr/mol berbentuk cair dalam suhu ruang karena adanya ikatan hidrogen yang antara molekul-molekul air, sehingga tiap molekul air akan tidak mudah terlepas dan berubah bentuk menjadi gas.
2. Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang baik. Sifat ini memungkinkan air tidak menjadi panas ataupun dingin dalam seketika. Perubahan suhu yang lambat ini mencegah terjadinya stress pada makhluk hidup akibat perubahan suhu yang mendadak dan juga memelihara suhu bumi agar sesuai dengan makhuk hidup.
3. Panas laten vaporisasi dan fusi yang tinggi. Panas laten vaporisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 gr pada suhu 20oC. Sedangkan panas laten fusi adalah energi yang dibutuhkan untuk mencairkan 1 gr es pada suhu 0oC. Besarnya energi panas laten vaporisasi adalah 586 cal dan untuk panas laten fusi adalah 80 cal. Tingginya energi yang diperlukan untuk menguapkan air ini penting artinya bagi tumbuhan dalam upaya menjaga stabilitas suhu daun melalui proses transpirasi.
4. Viskositas (hambatan untuk pengaliran) rendah. Karena ikatan-ikatan hidrogen harus diputus agar air dapat mengalir, maka ada anggapan bahwa viskositas air akan tinggi. Tapi pada kenyataannya tidaklah demikian, karena pada air dalam keadaan cair, setiap ikatan hidrogen dimiliki bersama-sama oleh dua molekul air lainnya, sehingga ikatan hidrogennya menjadi lemah dan mudah terputus. Inilah yang menyebabkan viskositas air rendah. Viskositas air yang rendah ini menyebabkan air menjadi pelarut yang baik, sifat ini memungkinkan unsur hara terlarut dapat diangkut ke seluruh jaringan tubuh makhluk hidup dan mampu mengangkut bahan-bahan toksik yang masuk dan mengeluarkannya ke luar tubuh.
5. Adanya gaya adhesi dan kohesi. Air bersifat polar sehingga gaya tarik menarik antara molekul air dengan molekul lainnya (misalnya dengan protein dan polisakarida penyusun dinding sel) akan mudah terjadi. Adhesi merupakan daya tarik menarik antara molekul air yang berbeda. Kohesi adalah daya tarik menarik antara molekul yang sama. Adanya kohesi dan adhesi ini menyebabkan air dapat diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan melalui jaringan xilem. Selain itu juga menyebabkan adanya tegangan permukaan yang tinggi, ini memungkinkan air mampu membasahi suatu bahan secara baik.
6. Air merupakan satu-satunya senyawa yang meregang ketika membeku. Ini berarti es memiliki kerapatan atau densitas (massa/volume) yang lebih rendah dibandingkan air. Dengan demikian es akan mengapung di atas air. Sifat ini mengakibatkan air permukaan yang berada di daerah beriklim dingin hanya membeku dipermukaan saja sehingga organisme akuatik masih bisa bertahan hidup.
b. Jenis –jenis air
Secara umum air yang terdapat di bumi ini digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:
1. Air tanah (ground water), adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan tidak dapat dilihat secara langsung. Air tanah ditemukan pada lapisan akifer yaitu lapisan yang bersifat porous (mampu menahan air) dan permeable (mampu memindahkan air). Pergerakan air tanah sangat lambat, kecepatan arus berkisar antara 10-10-10-3 m/detik sehingga waktu tinggal air (residence time) berlangsung lama. Air tanah ini dibagi menjadi dua jenis yaitu air tanah preatis dan air tanah artesis. Air tanah preatis adalah air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air/impermeable. Sedangkan air tanah artesis merupakan air tanah yang letaknya sangat jauh di dalam tanah serta berada di antara dua lapisan kedap air.
2. Air permukaan (surface water), adalah air yang terdapat di atas permukaan bumi dan tidak terinfiltrasi ke dalam bumi. Contoh air permukaan seperti laut, sungai, danau, kali, rawa, empang, dan lain sebagainya. Air permukaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu perairan tergenang (lentik) dan perairan mengalir (lotik). Perairan tergenang meliputi danau, waduk, kolam dan rawa. Pada umumnya perairan lentik ini dicirikan dengan arus yang lambat (0,001-0,01 m/detik) sehingga waktu tinggal air (residence time) dapat berlangsung lama. Perairan mengalir salah satunya adalah sungai, sungai dicirikan oleh arus yang searah dan relatif kencang dengan kecepatan arus berkisar antara 0,1-1,0 m/detik.
c. Sumber air
Secara umum ada beberapa sumber air yang dapat kita gunakan secara langsung atau melalui pengolahan sederhana terlebih dahulu yaitu antara lain :
1. Air dari PDAM. Air dari PDAM adalah termasuk air yang bisa dikonsumsi secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari: masak, mandi, mencuci; air PDAM yang akan diminum harus direbus dahulu. Namun air PDAM ini kadang belum tersedia diberbagai tempat.
2. Air hujan. Air hujan adalah air murni yang berasal dari sublimasi uap air di udara yang ketika turun melarutkan benda-benda diudara yang dapat mengotori dan mencemari air hujan seperti: gas (O2, CO2, N2, dll), jasat renik, debu, kotoran burung, dll. Air hujan yang berasal dari cucuran talang/genteng rumah di tampung dalam bak penampungan. Untuk mengindari bahan-bahan pengotor dan pencemar yang berasal dari talang/genteng dan udara caranya adalah waktu awal penampungan air hujan 15 menit setelah hujan turun. Di bawah talang diberi saringan dari ijuk/kerikil/pasir. Dan sebelum diminum air harus dimasak dahulu.
3. Mata air. Di daerah pegunungan atau perbukitan sering terdapat mata air. Air mata air berasal dari air hujan yang masuk meresap kedalam tanah dan muncul keluar tanah kembali karena kondisi batuan geologis didalam tanah. Kondisi geologis mempengaruhi kualitas air mata air, pada umumnya kualitasnya baik dan bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi harus dimasak sebelum diminum.
4. Air tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap dan tertahan di dalam bumi. Air tanah dapat dibagi menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Bagaimana mendapatkan air tanah caranya adalah dengan mengebor atau menggali. Macam sumur untuk mendapatkan air tanah adalah:
1. Sumur gali, adalah sarana mendapatkan air tanah dengan cara menggali dan menaikkan airnya dengan ditimba.
2. Sumur pompa tangan adalah sarana mendapatkan air tanah dengan cara mengebor dan menaikkan airnya dengan pompa dengan tenaga tangan.
3. Sumur pompa listrik adalah sarana mendapatkan air tanah dengan cara mengebor dan menaikkan airnya dengan dipompa dengan tenaga listrik.
5. Air permukaan. Air permukaan seperti air sungai, air rawa, air danau, air irigasi, air laut dan sebagainya adalah merupakan sumber air yang dapat dipakai sebagai bahan air bersih dan air minum tetapi perlu pengolahan. Air permukaan sifatnya sangat mudah terkotori dan tercemar oleh bahan pengotor dan pencemar yang mengapung, melayang, mengendap dan melarut di air permukaan. Karena sifatnya yang demikian maka sebelum diminum air permukaan perlu diolah terlebih dahulu sampai benar-benar aman dan memenuhi syarat sebagai air bersih atau air minum.
d. Siklus air (water cycle)
Karakteristik air dalam proses siklusnya secara fisik memperlihatkan berbagai fase, mulai dari bentuk uap air di udara sampai air dalam tanah. Secara meteorologis, air merupakan unsur pokok paling penting dalam atmosfer bumi. Air terdapat sampai pada ketinggian 12.000 hingga 14.000 meter. Bila seluruh uap air berkondensasi (atau mengembun) menjadi cairan, maka seluruh permukaan bumi akan tertutup dengan curah hujan kira-kira sebanyak 2,5 cm. Air terdapat di atmosfer dalam tiga bentuk yaitu dalam bentuk uap yang tak kasat mata, dalam bentuk butir cairan dan hablur es. Kedua bentuk yang terakhir merupakan curahan yang kelihatan, yakni hujan, hujan es, dan salju. Siklus air adalah mekanisme transformasi (pergerakan) air yang selalu terjadi setiap saat. Dalam proses transformasi biasanya desertai dengan perubahan wujud, sifat dan mutu ataupun air tetap dalam kondisi awal (Tersiawan, 2005). Secara garis besar transformasi itu dapat berupa evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi dan perkolasi.
Ketika terjadi hujan, airnya akan turun ke permukaan bumi. Air ini sebagian akan mengalir ke permukaan bumi menuju ke daerah yang lebih rendah dan bermuara di laut atau di danau. Sebagian lagi akan terserap oleh bumi dan mengalir di dalam tanah atau tersimpan di dalam tanah sebagai air tanah.
Siklus air ini digerakkan oleh matahari. Panas yang dipancarkan oleh matahari akan membuat air laut, air permukaan dan daratan menguap, bahkan air dari makhluk hidup pun ikut mengalaminya (evaporasi dan transpirasi). Ketika uap air mendingin dan menjadi mampat terbentuklah awan yang kemudian digerakkan oleh angin.
Angin ini akan membawa gumpalan-gumpalan awan ke daerah yang memiliki tekanan temperatur yang lebih rendah. Jika awan yang dibawa oleh angin ini melalui daerah pegunungan, maka gerakannya akan terhalang dan didorong untuk naik lebih tinggi lagi. Karena temperatur akan semakin rendah apabila semakin tinggi dari permukaan laut, maka awan yang mengandung uap air tadi mencapai titik embunnya dan terbentuklah butiran-butiran air yang kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai air hujan (presipitasi).
Air hujan ini akan mengalir lagi di permukaan bumi, ke daerah yang lebih rendah, dan sebagian diserap oleh bumi (perkolasi). Kemudian terus menuju ke laut atau ke danau dan apabila terkena sinar matahari akan menguap ke udara dan membentuk awan. Awan akan berkumpul dan kemudian dibawa oleh angin dan mengembun dan berubah menjadi hujan. Begitulah seterusnya siklus dari air yang berulang secara bergantian.